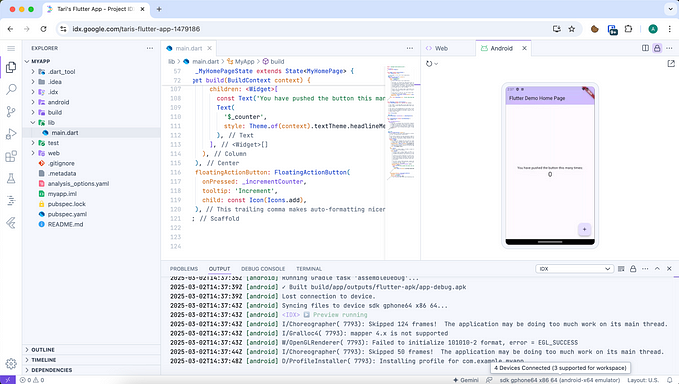Belajar Mikir Dulu Sebelum Baca

Berdasarkan survei dari Katadata Insight Center 60% masyarakat Indonesia terpapar hoax. Yang menyedihkan dari hoax adalah mereka yang terpapar hoax tidak sadar bahwa mereka mengkonsumsi berita hoax, sehingga perlu lingkungan sekitar untuk menyadarkan mereka bahwa berita tersebut hoax. Sayangnya hanya 21% — 36% masyarakat Indonesia yang bisa menganalisis hoax, jika mayoritas terpapar hoax, yang minoritas sangat sulit untuk membungkam mayoritas yang sudah mengkonsumsi hoax. Bahkan bisa menjadi lebih buruk lagi, ketika lingkungan sekitar kita mengkonsumsi berita hoax, maka yang tadinya kita kurang yakin dengan berita tersebut menjadi yakin karena mayoritas lingkungan kita menyatakan bahwa ini benar.
Hoax adalah informasi palsu, segala informasi yang palsu termasuk dalam hoax. Hoax tidak hanya berada di group Whatsapp keluarga kita masing-masing, tetapi ada di mana saja yang memungkinkan untuk menyalurkan informasi; buku, poster, postingan sosial media, video dan masih banyak lagi. Untuk itu agar kita tidak terpapar hoax dan bisa memahami isi informasi dengan baik kita memerlukan cara pikir yang baik dulu. Hoax sudah ada dari zaman ke zaman, sejak manusia sudah mulai bisa berbicara.
Buku Pertama

Sejak dahulu kala Informasi yang lengkap serta pengetahuan sudah disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk primitif seperti di tanah liat, gulungan kertas dan manuskrip yang ditulis menggunakan tangan sejak Raja dari Mesopotamia Kuno dan Firaun dari Mesir Kuno. Pada awalnya penggunaan dokumen tertulis bukan lah digunakan untuk membuat kisah cinta yang menyayat hati, maupun puisi-puisi indah. Pada awal manusia mulai mengembangkan teknologi tulisan, yang tertulis hanyalah fakta dan angka. Peninggalan peradaban Sumer 3400–3000 SM yang pertama kali mengembangkan tulisan bukanlah cerita novel, dan bukan pula kata-kata bijak dari Raja terdahulu mereka tetapi tulisan pertama yang diketahui yang tertulis diatas lempeng batu adalah “29.086 takaran jelai diterima selama 37 bulan. Tertanda, Kushim.” Huruf yang digunakan juga bukan huruf yang kita lihat sehari-hari tetapi huruf primitif.
Dokumen paling awal yang diketahui manusia yang paling mirip dengan buku modern dikenal sebagai Codexes. Codex dikembangkan oleh kerajaan roma untuk menggantikan gulungan kertas, bentuk Codex hampir mirip dengan buku jaman sekarang, masing-masing lembar di sambung satu persatu. Sejak Perpustakaan Alexandria hingga biara-biara di Eropa selama Abad Pertengahan, dokumen tertulis disalin, didekorasi, dan dicetak ulang dengan tangan di ruang kerja yang disebut scriptoria. Manuskrip yang diterangi ini adalah karya tulisan tangan yang indah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan oleh para biarawan.

Bertahun-tahun kemudian, pada 1454, seorang pria Jerman bernama Johannes Gutenburg membangun mesin cetaknya sendiri (dan pertama di dunia), atau mesin cetak bergerak. Ini mengubah segalanya dalam semalam, karena buku dapat dicetak jauh lebih mudah dan lebih cepat.

Semakin Cepat Semakin Baik?
Pada awalnya sebelum ada teknologi mesin cetak, orang-orang membuat buku menggunakan tulisan tangan. Hal ini membuat harga buku pada jaman dulu cukup mahal, serta proses pembuatan untuk dicetak secara masif dan dipasarkan cukup lama. Bahkan jika seseorang memiliki buku, sudah bisa di cap orang kaya oleh orang-orang sekitar, buku pada waktu itu layaknya tas Luis Vuitton. Tetapi setelah teknologi mesin cetak sudah ditemukan informasi perlahan-lahan semakin cepat, harga buku pelan-pelan semakin terjangkau. Hal ini menjadi anugerah yang sangat indah pada masanya.
Apakah Benar Anugerah?
Muncul nya teknologi mesin cetak pada waktu itu, sama gemparnya dengan penemuan internet. Informasi yang tadi sudah cukup cepat, menjadi tambah cepat lagi dengan adanya internet. Sayangnya semakin cepatnya penyebaran informasi, maka makin cepat pula penyebaran berita hoax. Jika kalian berpikir berita hoax adalah hal yang baru ada di era internet, kalian salah besar. Informasi palsu sudah ada sejak dulu. Maupun buku dan internet adalah salah dua media yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Sayangnya informasi bukan berarti itu kebenaran. Berita hoax, novel, jurnal ilmiah, dan film juga adalah informasi. Hampir setiap hari kita menyerap informasi, tetapi pertanyaannya apakah kita menyerap informasi yang benar?
Buku Viral Pada Masanya
Sekitar tahun 1400an sampai 1500an ada sebuah buku yang menggemparkan Eropa. Penjualan buku ini melampaui penjualan buku manapun kecuali alkitab. Buku yang dijual ini bukanlah buku novel, atau pemenang nobel, buku terlaris di Eropa adalah The Hammer of Witches karyanya Malleus Malleficarum. Buku ini bukan novel agung layaknya bukunya Shakespeare. Buku ini memberi tips & trick cara menghancurkan dan mendeteksi penyihir. Buku ini bertanggung jawab atas pembataian orang-orang tak bersalah yang dituduh sebagai penyihir.
Mereka juga sama dengan kita di masa sekarang. Ketika mereka menyampaikan informasi, atau membaca informasi mereka akan langsung menyebarkannya. Mereka akan mengatakan “ini benar karena saya lihat di buku” kurang lebih sama dengan kita “ini benar karena saya lihat di youtube” Bukan berarti jika sebuah informasi berada di buku maupun internet itu menjadi benar. Inilah kenapa sebelum kita membaca buku, sebaiknya kita memperbaiki dulu cara pikir kita. Mau setinggi angkasa tumpukan buku yang sudah kita bacapun, jika cara pikir kita berantakan ini tidak akan memberi manfaat apa-apa dengan kita. Kita jadi tidak bisa menganalisis suatu hal, kita tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, kita gampang termakan hoax, dan masih banyak lagi kerugian yang kita dapatkan. Kalau seperti itu, ya kita kurang lebih sama saja seperti Google, banyak informasi tetapi tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah.
Otak Yang Mengolah Informasi
Otak adalah hardware
Informasi adalah software
Agar hardware berjalan dengan baik dibutuhkan software yang mumpuni.
Bayangin otak kita itu adalah motherboard atau otaknya laptop, terus kita ingin membuka software Microsoft Word misalnya. Eh, laptop kita ngelag, terus error pula. Kita ngeliat aplikasi di laptop kita, ada banyak banget dan ada yang bagus ada yang jelek. Dalam hati kita terbesit “hadeh gimana mau buka yang lain, Microsoft Word aja error melulu”. Nah, seperti itulah gambaran otak kita percuma kita punya triliunan informasi, tetapi otak kita belum mumpuni buat menerapkan, menganalisis, dan menguji informasi yang kita simpan. Percuma. Seperti laptop tadi, aplikasinya banyak banget, tetapi mau buka Microsoft Word aja error, gimana mau buka yang lain.
Untuk itu kita perlu mengasah otak kita, sebelum kita membaca buku yang banyak. Mengasahnya bukan pakai pisau, tenang aja. Mengasahnya menggunakan Scientific Thinking (penalaran ilmiah) serta logika dasar. Kalau kata Tan Malaka pahlawan sekaligus pemikir Indonesia favorit saya.
“Begitulah juga otak yang sudah dilatih oleh matematika, lain sikapnya terhadap suatu persoalan daripada otak mentah.”
Madilog-Tan Malaka
Matematika yang dimaksud Tan Malaka bukan kalau kita hafal rumus aljabar itu bikin otak kita tajam, bukan begitu. Yang Tan Malaka maksud adalah cara pengerjaan matematikanya, metodenya. Logika sama matematika itu seperti adik beradik yang tak pernah lepas, logika dan matematika adalah contoh sesuatu yang terstruktur dan rapi, jika tidak terstruktur maka hasilnya akan salah. Makanya jika kita berlatih terus menerus menggunakan penalaran ilmiah, serta logika, maka otak kita juga bisa menggunakan informasi dengan baik dan benar, tepat seperti yang Tan Malaka bilang.
Scientific Thinking
Pengertian penalaran ilmiah atau scientific thinking itu; suatu proses berfikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, atau petunjuk menuju suatu kesimpulan. Penalaran ilmiah adalah proses berfikir yang sistematis dan logis untuk memperoleh sebuah kesimpulan atau informasi yang sebelumnya tidak diketahui. Penalaran ilmiah adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan bukti empiris. Empiris adalah segala sesuatu yang dapat diuji serta dapat diamati.
Salah dua contoh yang berguna dari penalaran ilmiah adalah Induksi dan Deduksi. Induksi serta Deduksi sering dipakai bukan hanya oleh para ilmuan tetapi hampir semua manusia untuk mencapai suatu kesimpulan ketika mengamati suatu fenomena atau peristiwa. Hanya kita tidak sadar saja, bahwa itu adalah penalaran induksi & penalaran deduksi.

Induksi serta Deduksi diperlukan agar pembaca dapat menerapkan isi buku, atau menguji keadaan di realita. Hal ini dapat berlaku sebaliknya juga.
Induksi
Suatu peristiwa yang spesifik diterapkan secara universal.
Sebagai contoh begini, kamu mengamati ternyata pembelian pasta gigi anti duren meningkat. Kamu merenung persoalan ini cukup lama, kamu tidak bisa tidur membayangkan fenomena yang membingungkan ini, kenapa pasta gigi anti duren meningkat? Lalu pada suatu malam bulan purnama kamu mengambil kesimpulan, bahwa setiap pembeli pasta gigi anti duren di musim duren akan meningkat. Nah, kesimpulan yang baru kamu ambil itu namanya Induksi.
Kalau masih belum paham, mari kita bedah pake contoh gambar yang diatas ya.
1.Observation/Observasi
Kamu ngeliat kok pembeli pasta gigi anti duren meningkat ya, biasanya gak begini.
2. Pattern/Pola
Kamu ngeliat lagi, eh ternyata ada polanya nih penjualan pasta gigi anti duren meningkat hanya disaat musim duren.
3. Hypotesis/Pendugaan
Habis kamu ngeliat pola dan observasi kamu menduga nih, bahwa setiap musim duren pembelian pasta gigi anti duren akan meningkat. Lalu setelah melihat segala macam bukti, itu sejalan dengan perdugaan kamu. Misalnya, ketika bukti yang kamu kumpulkan ternyata tidak sejalan dengan apa yang kamu duga berarti hipotesis kamu runtuh, dan tidak bisa ke tahap selanjutnya.
4. Theory/teori
Setelah kamu melihat bahwa bukti yang kamu kumpulkan sudah cukup kuat, maka pernyataan kamu menjadi teori. Kamu hampir bisa menjamin bahwa berdasarkan bukti yang saya kumpulkan dan cari, bahwa setiap musim duren pembelian pasta gigi anti duren akan meningkat.
Induksi biasanya bisa digunakan juga untuk memprediksi suatu fenomena. Ketika kamu sudah mengambil kesimpulan “bahwa setiap pasta gigi anti duren di musim duren akan meningkat” maka kamu bisa memprediksi berdasarkan bukti ini, serta data ini, maka musim duren tahun depan pasta gigi juga akan meningkat.
Induksi biasanya juga sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita pencet tombol like di instagram, kita ngeliat nih setiap kita tap 2 kali di post orang yang kita follow di instagram bakal muncul hati warna merah. Kita kaget, “apa nih kok muncul hati” terus kita coba lagi, eh muncul lagi. Setelah berulang-ulang coba kita ambil kesimpulan deh “Setiap sentuh dua kali di post instagram, maka akan muncul hati warna merah”
Untuk mempermudah apa sih induksi? saya selalu membayangkan Sherlock Holmes seorang detektif yang mengamati dulu, baru mengambil kesimpulan dan berani menyatakan bahwa orang itu salah.
Deduksi
Suatu yang bersifat universal diterapkan terhadap fenomena yang spesifik.
Deduksi adalah kebalikannya dari Induksi. Sebagai contoh begini, ada yang menyatakan bahwa “setiap orang yang terjun dari lantai 100 maka akan mati” kamu bilang “ah masa sih” kamu masih butuh pembuktian. Besoknya kamu melakukan eksperimen, kamu pergi ke lantai 100 dan kamu memutuskan terjun. Waktu udah sampai ke bawah ternyata kamu beneran mati. Nah, ini namanya Deduksi. Tahapnya ya kebalikan dari induksi.
Contoh deduksi terkenal dari Aristoteles:
P1: Semua manusia akan mati.
P2: Joko manusia
K : Maka joko akan mati.
Untuk mempermudah saya apa sih deduksi? saya selalu membayangkan seorang anak yang cukup nakal. Udah dibilangin sama orang tua masih aja ngeyel. Bisa juga sebagai ilmuan yang melakukan eksperimen. Biasanya Deduksi digunakan untuk pembuktian suatu klaim.
Kenapa Diperlukan Scientific Thinking?
Penalaran ilmiah atau scientific thinking akan sangat membantu ketika membaca buku, terlebih lagi buku non-fiksi. Ketika membaca buku tentu ada data yang bisa kita lihat, data ini bisa kita terapkan dan bisa kita uji. Misalnya ketika saya sedang membaca buku bisnis yang mengatakan “semua usaha yang sukses dimulai dengan orang tua yang kaya” nah pernyataan buku itu adalah penalaran induksi karena bersifat universal. Karena buku tersebut menyatakan “semua usaha yang sukses dimulai dengan orang tua yang kaya”. Kebetulan misalnya saya lahir dari keluarga yang kaya, maka saya bisa memprediksi bahwa saya akan kaya.
Bukan hanya itu yang bisa kita manfaatkan ketika belajar tentang penalaran ilmiah, dengan deduksi kebalikan dari induksi kita bisa menguji suatu klaim dari buku yang kita baca itu benar atau tidak. Misalnya pake contoh yang tadi “semua usaha yang sukses dimulai dengan orang tua yang kaya” ketika habis membaca itu kamu kaget dan berdesit dalam hati “masa sih, semua usaha yang sukses dimulai dari orang tua yang kaya” nah, disini bisa dilakukan deduksi. Kamu lihat sekeliling kamu misalnya ada 3 orang yang usahanya sukses, ada si; Joko, widodo, dan Amin. Setelah itu, kamu cari tau tentang latar belakang keluarganya yang pertama si Joko, kamu liat ternyata benar dia terlahir dari orang tua yang kaya, terus kamu liat si Widodo ternyata oh ternyata dia lahir dari keluarga yang kurang mampu. Nah, kamu gak perlu lagi nyari deh si Amin ini beneran dari keluarga orang kaya apa enggak. Karena cukup satu orang saja, udah bisa matahin klaim dari buku yang bilang “ Semua usaha yang sukses dimulai dengan orang tua yang kaya”.
Nah, udah liat kan. Induksi serta Deduksi bakal sangat ngebantu kita, dalam menganalisis, menerapkan dan menguji suatu pernyataan. Metode penalaran ilmiah ini adalah alat yang bisa kita gunakan maupun tidak. Sama seperti setrika kita bisa milih mau merapikan baju menggunakan setrika atau pake tangan. Kamu boleh milih mau pake cara apa, tetapi jelas bahwa yang lebih efisien, rapi dan terbukti ampuh dalam merapikan adalah setrika.
Bagaimana Kita Tahu Bahwa Yang Kita Tahu Benar?
Kalian pernah mikir gak sih, di dunia yang informasi serba cepat begini saling simpang siur, gimana kita tahu mana yang benar mana yang salah?
Disini metode ilmiah bisa diterapkan juga untuk menganalisis berita, serta informasi yang masuk ke diri kita. Metode ilmiah adalah metode yang berbasis bukti dan tahan uji. Dongeng, novel, dan buku pelajaran juga informasi.
Tetapi bagaimana kita tahu kalau ini benar, sedangkan ini salah?
Bukti
Bukti terbukti ampuh untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Gak usah jauh-jauh bentuk bumi, organ tubuh manusia, bintang, luas angkasa, dan kedalaman laut diketahui karena bukti. Bukti terbagi menjadi dua, bukti yang bisa diuji serta bukti yang tidak bisa diuji. Bukti yang bisa diuji adalah bukti ilmiah, yaitu bukti yang bisa diamati serta diuji. Sedangkan bukti yang tidak bisa diuji adalah bukti yang diluar dari ilmiah, tidak bisa diamati dan tak bisa diuji. Contohnya begini;
- Bukti yang bisa diuji
Saya mempunyai kambing, jika kalian tidak percaya silahkan datang kerumah saya kalian amati dan uji bahwa hewan yang dirumah saya adalah kambing.
Kambing saya kakinya jadi 5 ketika saya beri makan kacang, jika kalian tidak percaya silahkan datang kerumah saya kalian amati dan uji bahwa hewan yang dirumah saya setelah makan kacang kakinya jadi 5.
- Bukti yang tidak bisa diuji
Saya mempunyai kuda terbang, tetapi hanya saya yang bisa melihatnya kalian tidak bisa.
Saya bisa melihat hantu, tetapi hanya orang terpilih yang bisa melihatnya.
Bukti bukan hanya melulu soal hal-hal seperti itu, bukti bisa kita gunakan untuk menganalisis kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ada yang menyatakan “makan 1 kali sehari bikin perut sixpack” saya tidak perlu langsung mencobanya, saya lihat saja data serta bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Apakah valid atau tidak. Misalnya ternyata bukti, serta data yang diambil mendukung pernyataan orang tersebut, maka kita boleh saja mencobanya. Kalau kita kurang yakin kita boleh ke tahap selanjutnya yaitu pengujian. Setelah kita uji berkali-kali ternyata selaras dengan yang apa dikatakan orang tersebut, maka boleh kita pastikan bahwa pernyataan orang tersebut bisa dipertanggung jawabkan.
Pengujian tidak melulu tentang harus ke laboratorium dan hal-hal yang ilmuan gunakan. Pengujian bisa kamu lihat di lingkungan kamu sendiri, mulai dari keluarga atau teman kamu. Kamu lihat aja sekeliling kamu, kamu cari orang yang perutnya sixpack terus diamati apakah dia sixpack karena makan sekali sehari? Setelah 10 orang yang kamu amati, ternyata 9 orang sixpack karena olahraga dan makan 3 kali sehari, sedangkan 1 orangnya sixpack karena makan sekali sehari saja. Nah, pernyataan bahwa “makan 1 kali sehari bikin perut sixpack” tidak dapat diandalkan atau unreliable. Tingkat reliability klaim tersebut hanya 10%. Sebaiknya jika kita menemukan klaim atau bukti dengan tingkat reliability yang dibawah 80% maka perlu kita pertanyakan keandalannya. Lah, kok gitu? iya dong. Bayangin aja misalnya ilmuan berhasil membuat taksi ke luar angkasa, semua orang boleh naik. Tapi dari 1000 penerbangan 500 nya kecelakaan. Nah, ini perlu kita pertanyakan karena tingkat reliability (keandalan) dari taksi luar angkasa hanya 50%. Sama kayak vaksin, misalnya kalau ada 1000 orang yang divaksin, tetapi yang meninggal ada 2. Berarti vaksin terbukti dapat diandalkan karena tingkat reliabilitynya yaitu 99%. Hal ini banyak bisa kita lihat di sekeliling kita, misalnya papan ketik dari gadget kita, kalau kita pencet “A” maka yang keluar mestinya “A” dengan cara ini papan ketik pada gadget kita, bisa kita buktikan dapat diandalkan atau tidak.
Falsifikasi
Ini salah satu metode ilmiah yang menurut aku ngebantu banget, dalam menemukan suatu “kebenaran”. Falsifikasi adalah pembuktian suatu klaim/bukti itu salah. Menurut Karl Popper yang membedakan ilmu ilmiah dengan yang lainnya adalah kemampuan ilmu ilmiah untuk membuktikan dirinya salah. Suatu pernyataan ilmiah itu kuat bukan hanya karena banyaknya bukti yang mendukungnya, tetapi karena tidak ditemukan bukti kesalahannya.
“Suatu teori/pernyataan bisa disebut ilmiah jika bisa terdapat kemungkinan untuk menyangkalnya.”
The Logic of Scientific Discovery — Karl Popper
Pernyataan ilmiah tuh bukan soal, gravitasi, evolusi, serta struktur atom aja. Pernyataan ilmiah adalah segala pernyataan yang bisa dibuktikan kesalahannya. Jika pernyataan memiliki kemungkinan untuk dibuktikan kesalahannya, itu namanya falsifier potential atau potensi kesalahan. Setiap hari kita diasupi dengan pernyataan ilmiah, cuma kita gak sadar aja.
Langsung contoh aja kali ya.
Pernyataan Ilmiah:
Pernyataan Ilmiah: Semua lelaki itu brengsek.
Falsifier Potential : Ada lelaki yang tidak brengsek.
Falisifier Potential atau potensi kesalahan itu gak perlu ada, tetapi cukup kemungkinan ada aja. Kalau misalnya kita udah cari-cari nih, mana ya lelaki yang tidak brengsek. Ternyata gak ketemu, berarti pernyataan ilmiah itu benar dan kuat. Kalau dimasa depan kita ketemu satu aja lelaki yang tidak brengsek, berarti pernyataan tersebut runtuh. “Lah, bukannya hitung reliabilitynya?” untuk kali ini enggak, karena pernyataan tersebut universal “Semua”. Nah, kalau pake kata “semua” perlu cari satu aja untuk membuktikan kesalahannya. Kalau seperti vaksin, mobil, pesawat luar angkasa, six pack makan sekali sehari, itu bisa kita ukur dari tingkat reliabilitynya karena tidak menggunakan jaminan universal yaitu kata “semua”.
“Tidak ada jumlah yang cukup untuk membuktikan bahwa semua angsa itu putih. Cukup dibutuhkan satu angsa hitam untuk menyangkalnya.”
The Logic of Scientific Discovery — Karl Popper
Pernyataan non-ilmiah atau tidak bisa dibuktikan kesalahannya adalah pernyataan yang tak bisa ditemukan kemungkinan untuk salahnya. Jika suatu pernyataan tidak bisa dibuktikan kesalahannya maka pernyataan tersebut juga tidak bisa benar. Pernyataan yang sifatnya multi tafsir, tidak jelas, dan tidak bisa disalahkan Ini namanya Unfalsiable Claim, klaim yang tidak bisa disangkal. Langsung ke contoh aja kali ya.
Pernyataan Non Ilmiah:
Pernyataan non ilmiah: Besok bisa hujan dan tidak hujan
Falsifier potential : Kosong
Karena apapun yang terjadi besok, ya tetap benar. Contoh lain lagi deh.
Pernyataan non ilmiah: oh bumi, kau bulat bagaikan bola, datar bagaikan meja.
Falsifier Potential : Kosong
Dengan asumsi bahwa pilihan bentuk bumi hanya bulat & datar, maka pernyataan tersebut tidak bisa benar, dan tidak bisa salah. Karena apapun tafsirnya ya tetap benar.
Menerapkan Falsifikasi Dalam Kehidupan
Setelah kita mengetahui, bahwa untuk membuktikan suatu pernyataan benar kita bisa membuktikan kesalahannya, dan perbedaan pernyataan yang bisa benar dan bisa salah, serta yang tidak bisa benar dan salah sama sekali. Sekarang mari kita cari tahu apa aja yang bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari.
Falsfikasi mengajarkan kita, untuk mencari suatu kebenaran jangan mencari bukti yang mendukung kita saja, tetapi mencari bukti yang membuktikan kita salah. Kalau kata astrofisikawan favorit saya;
“Salah satu tantangan terbesar di dunia ini adalah mengetahui banyak tentang sesuatu yang kamu pikir benar, tetapi tidak mengetahui apapun tentang sesuatu untuk mengetahui kita salah.”
Neil deGrasse Tyson
Kalau direnungin lagi kata om Neil ada benernya juga kan? Kita cenderung nyari informasi yang kita pengen atau yang kita percaya benar aja. Kita gak pernah mencari informasi yang mengatakan kita salah. Jika kalian terjebak dalam cara berpikir seperti ini, berarti kalian terjebak dalam bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu terjadi ketika memverifikasi pernyataan atau argumen yang kita dukung aja, ketika ada yang membuktikan kita salah, kita tidak peduli.
Kita harus selalu skeptis (sikap ragu terhadap sesuatu) terhadap segala hal yang ada di dunia ini. Selalu membuka kemungkinan kalau kita salah. Skeptis bukan sembarang skeptis, misalnya orang pake vaksin kita anti vaksin, orang pake masker kita anti masker, ini bukan skeptis yang baik. Jaman sekarang orang cuma banyak yang skeptis, tetapi skeptisnya skeptis yang buruk tidak berlandaskan apapun. Mereka hanya ingin keraguan mereka yang benar, mau kita kasi bukti, data, jurnal ilmiah, riset yang dapat diuji tetap saja mereka tidak yakin.
“Skeptis yang baik mempertanyakan apa yang dia tidak yakin, tetapi menjadi yakin lagi ketika sudah menemukan bukti valid akan pertanyaannya itu.”
Factfulness — Hans Rosling
Jadi ikutin pesan dari kakek Hans kita harus skeptis, tetapi jadilah skeptis yang baik.
Coba deh sesekali kita uji argumen kita, seluruh argumen yang kita anggap benar. Jangan melalui metode verifikasi (pembuktian kebenaran) tetapi falsifikasi (pembuktian kesalahan) uji terus, karena ketidakmauan kita untuk mengetahui hal yang tidak kita setujui mempersempit pandangan kita akan suatu hal. Selalu falsifikasi argumen kita, jangan pernah berhenti dan mengatakan “nah ini benar” tetapi katakan “untuk saat ini, ini benar”.
“Manusia adalah mangsa bagi kebenarannya. Begitu mereka mengakuinya, mereka tidak akan pernah bebas dari itu.”
The Myth of Sisyphus — Albert Camus
Selalu buka kemungkinan bahwa semua argumen yang kita percayai benar akan bisa salah sewaktu-waktu, jangan berpegang teguh sama suatu argumen jika bukti menyatakan bahwa itu salah. Jika semua bukti yang bisa kita uji, menyatakan bahwa kita salah tetapi kita masih menyatakan bahwa argumen kita ini benar berarti ego kita lebih besar daripada kebijaksanaan kita.
Falsfikasi → Falsifikasi → Falsifikasi → Falsifikasi → Falsifikasi → Falsifikasi → ?
Selalu falsifikasi setiap hasil falsifikasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Tanda tanya di akhir itu adalah keadaan dimana kita, belum menjumpai bukti yang kuat untuk merobohkan hasil falsifikasi kita sebelumnya.
Kadang di awal untuk menerapkan metode ilmiah, cara berpikir yang rasional serta logis dalam kehidupan sehari-hari akan terasa berat. Seiring berjalannya waktu semakin kita sering menerapkan pikiran yang baik dalam menganalisis informasi yang masuk, maka usaha yang kita gunakan tidak akan sebesar disaat pertama kali kita mencobanya. Seperti bermain sepeda, saat pertama kali kita menaiki sepeda tentu ada jatuh bangun, mulai dari roda 3, pelan-pelan roda 2, hingga pada akhirnya kita tidak butuh usaha yang besar untuk berusaha mengimbangkan diri kita diatas kendaraan roda dua itu. Hal yang sama pasti pula bisa kita terapkan dengan cara berpikir kita. Jikalau kamu merasa lelah, percaya deh ini sangat berguna bukan hanya untuk kamu seorang, tetapi berguna demi keberlangsungan peradaban.
“Science itu tidak memandang warna atau bentuk badan. Di mana alatnya sedia di sana akan maju!”
Madilog- Tan Malaka
Source:
Sapiens — Yuval Noah Harari
Madilog — Tan Malaka
The Logic of Scientific Discovery — Karl R. Popper
Factfulness — Hans Rosling, Ola Rosling, & Anna Rosling
https://www.thebalancecareers.com/inductive-reasoning-definition-with-examples-2059683
https://qz.com/1183992/why-europe-was-overrun-by-witch-hunts-in-early-modern-history/
https://www.geo.sunysb.edu/esp/files/scientific-method.html
https://pitt.libguides.com/historybooksprinting/originsofthebook